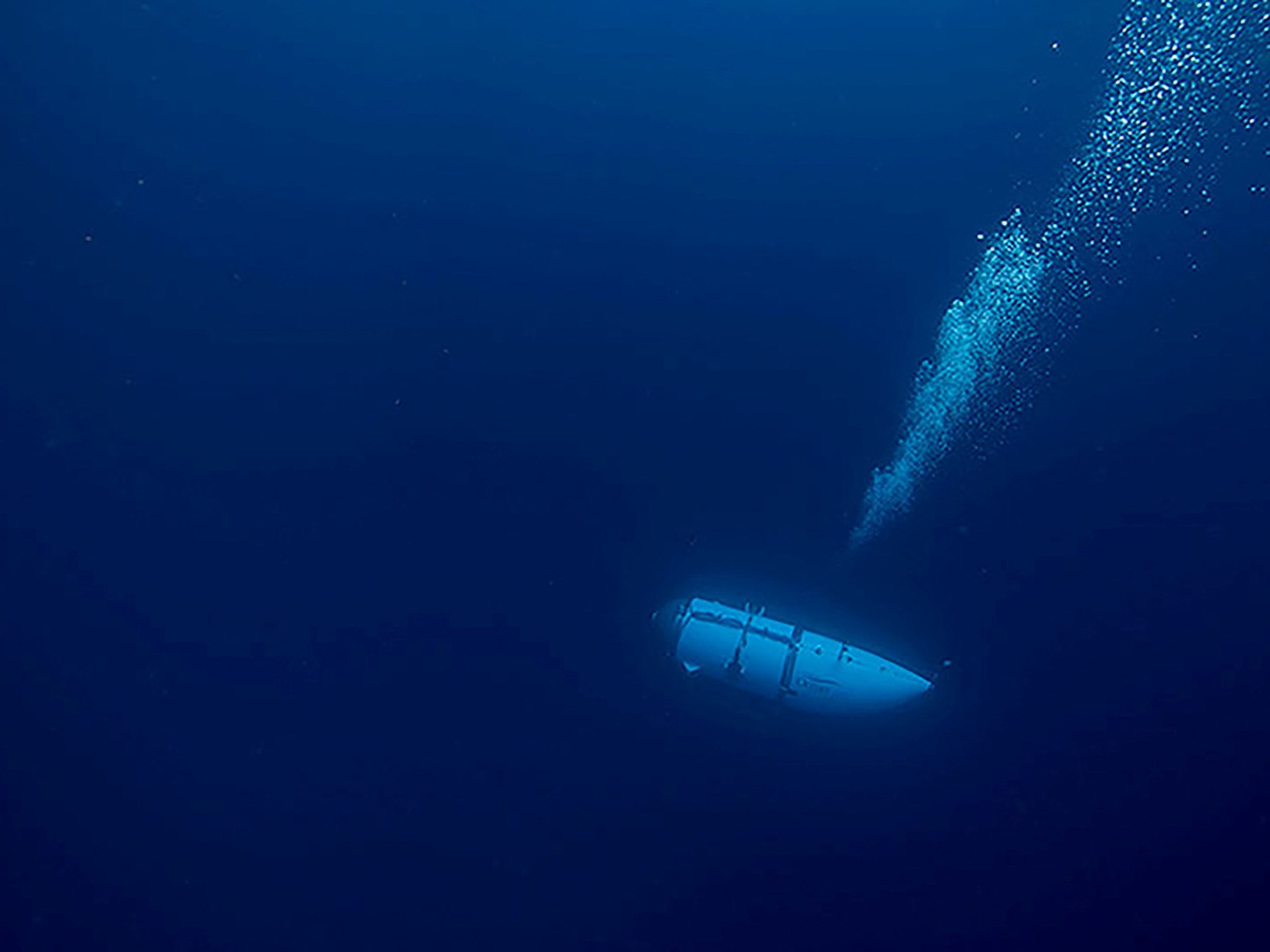Akhir-akhir ini “persinggungan” tampaknya menjadi kata di bibir setiap orang.
Itu meledak dalam wawancara oleh para pakar dan politisi, dinyanyikan oleh aktivis aktivis, dibawa ke berita utama oleh jurnalis dan ditulis dengan huruf tebal di dinding kampus oleh mahasiswa progresif.
Tapi apa arti sebenarnya dari istilah yang tampaknya mencakup segalanya ini?
“Interseksionalitas” diciptakan pada tahun 1989 oleh aktivis hak-hak sipil Amerika dan sarjana hukum feminis Kimberlé Crenshaw. Dalam wawancara baru-baru ini dengan majalah Time, dia hanya menggambarkannya sebagai “sebuah lensa, sebuah prisma, untuk melihat bagaimana berbagai bentuk ketidaksetaraan sering bekerja sama dan saling memperburuk”.
Namun dalam tiga dekade sejak awal, telah terjadi distorsi besar dalam arti istilah tersebut.
“Feminisme saya akan menjadi titik-temu, atau itu akan menjadi omong kosong,” kata komentator budaya Flavia Dzodan dalam posting blog 2011. pernyataan telah menjadi slogan Internet yang terkenal—semacam seruan untuk apa yang disebut “feminis modern” yang mengkritik feminisme generasi sebelumnya karena terlalu fokus pada hak-hak perempuan dan kekerasan laki-laki terhadap perempuan.
Dzodan, yang menganjurkan dekriminalisasi perdagangan seks secara umum dan melabeli mereka yang ingin menghapusnya “fobia pelacur“, segera dilihat sebagai perwakilan terkemuka dari “feminisme interseksional” dan membantu istilah yang diciptakan oleh Crenshaw perlahan-lahan kehilangan semua maknanya.
Menurut pendapat saya, Dzodan dan seharusnya “feminis interseksional” seperti dia benar-benar salah menafsirkan apa yang dimaksud Crenshaw dengan interseksionalitas. Tidak seorang pun yang benar-benar memahami interseksionalitas dan ingin mengurangi efek tumpang tindih dari berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh individu yang terpinggirkan, dan terutama perempuan yang terpinggirkan, dapat mendukung perdagangan seks. Perempuan miskin, berkulit hitam, berwarna, dan pribumi secara signifikan terwakili secara berlebihan di pasar prostitusi global. Saya melakukan wawancara lusinan wanita kulit berwarna yang lolos dari perdagangan seks, semuanya mengatakan kepada saya bahwa pembeli seks memperlakukan mereka dengan sangat hina.
Yang terbaik, feminisme selalu mendukung prinsip yang sekarang dikenal sebagai interseksionalitas. Memang, mengatasi kerugian kumulatif yang ditimbulkan pada individu yang terpinggirkan oleh berbagai bentuk penindasan (terkait dengan ras, disabilitas, dan kelas serta jenis kelamin) selalu menjadi dasar praktik sebagian besar feminis yang bijaksana.
Tetapi sekarang orang semakin menggunakan konsep “interseksionalitas” untuk menggambarkan keluhan yang mereka alami sebagai akibat dari identifikasi diri mereka sebagai “poliamori”, “non-biner”, “cairan gender”, atau identitas atau orientasi baru lainnya. . Sementara label “pekerja seks” dijual kepada kita sebagai identitas lain yang seharusnya dianut dan dilindungi di bawah payung feminisme titik-temu.
Semua ini merupakan penghinaan terhadap istilah yang diciptakan oleh Crenshaw.
Politik identitas telah menciptakan feminisme merek baru, dan pemahaman baru tentang “interseksionalitas”, yang tidak lain adalah latihan narsisme yang memusatkan individu (yang diistimewakan) dan mengabaikan penindasan institusional yang sebenarnya.
Sebagai hasil dari pemahaman baru yang terpelintir tentang “interseksionalitas” ini, di Inggris kita sekarang menghadapi kenyataan di mana lusinan lesbian kelas pekerja, banyak di antaranya berkulit berwarna, dituduh, sebagian besar oleh siswa kulit putih yang sangat istimewa, melakukan penindasan. pria kelahiran kulit putih yang mengidentifikasi diri sebagai “non-biner”, “aseksual”, atau trans. Kami dituduh sebagai “fanatik” atau “bukan feminis sejati” karena kami menolak untuk mendahulukan kepentingan dan perasaan orang-orang kelahiran laki-laki dengan identitas apa pun di atas kebutuhan perempuan dan anak perempuan.
Ketika para siswa yang begitu terikat pada garis “pekerjaan seks adalah pekerjaan” menggunakan konsep interseksionalitas untuk menyerang kaum feminis yang berkampanye untuk mengakhiri kekerasan laki-laki, mereka secara tidak sengaja memberikan dukungan kepada mucikari dan pengeksploitasi perempuan lainnya.
Ketika saya baru-baru ini menghadiri konferensi di Kanada dengan nomor Penduduk asli yang selamat kekerasan laki-laki, misalnya, kami dihadang oleh pengunjuk rasa yang memegang plakat dan berteriak melalui pengeras suara: “Pekerja seks adalah pekerjaan” dan “Pekerjaan pukulan adalah pekerjaan nyata”. “Di sini hidup feminisme titik-temu!” teriak penonton sambil melambai-lambaikan plakat ke arah pembicara dan delegasi saat kami memasuki venue.
Itu tidak bisa dilanjutkan.
Feminisme adalah – atau setidaknya sekali – satu-satunya gerakan politik di planet ini yang memprioritaskan perempuan dan anak perempuan dan berjuang terutama (jika tidak secara eksklusif) untuk mengakhiri penindasan patriarki. Adalah tugas kita sebagai feminis untuk memastikan bahwa gerakan kita tetap setia pada dirinya sendiri. Kami sangat perlu memfokuskan kembali feminisme kami untuk menempatkan perempuan sebagai pusatnya.
Tak perlu dikatakan bahwa interseksionalitas – interseksionalitas sejati seperti yang pertama kali didefinisikan oleh Crenshaw sekitar tiga dekade lalu – harus tetap menjadi inti dari gerakan kita. Dalam perjuangan untuk hak dan keamanan ini, wanita di bawah tangga, wanita yang merasakan beban dari berbagai penindasan yang tumpang tindih di pundak mereka, lebih penting daripada mereka yang membenturkan kepala ke langit-langit kaca perusahaan, mengeluh bahwa mereka “hanya satu juta menghasilkan” ” sementara rekan pria mereka menghasilkan lebih banyak. Bukan berarti para wanita itu bukan korban seksisme – hanya saja penderitaan mereka jelas kurang mendesak dibandingkan dengan wanita yang berjuang untuk memberi makan anak-anak mereka, yang menghadapi rasisme dan bentuk diskriminasi lainnya di atas penindasan yang mereka derita karena mereka perempuan. .
Apa yang sekarang kita sebut politik identitas, di mana pemahaman yang terdistorsi tentang “interseksionalitas” telah menjadi komponen yang menentukan, lahir pada 1980-an dari kiri politik, sebagai tanggapan terhadap gerakan keadilan sosial mayoritas kulit putih yang didominasi menengah pada saat itu. -pria kelas. Ini selalu menjadi masalah bagi kaum kiri: sementara kaum kanan tidak menyesali apa yang dilihatnya sebagai “tatanan alami” dari berbagai hal (di mana kelas dan hak istimewa ras hanyalah masalah fakta dan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan), kaum kiri sering mengklaim mewakili berbagai komunitas dalam masyarakat, bahkan jika para pendukungnya yang memiliki hak istimewa sering melakukan sedikit upaya untuk menjauh dari pusat perhatian sehingga kaum terpinggirkan dapat dilihat dan didengar.
Ini jauh dari sempurna, tetapi dalam sejarahnya yang panjang, gerakan feminis tidak pernah didorong oleh yang diistimewakan. Feminisme adalah gerakan akar rumput yang dimulai dengan perempuan yang mengalami penindasan paling mengerikan—seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan pelecehan anak—menuntut sebuah platform untuk membuat suara mereka didengar.
Saat ini ada orang (dari kedua jenis kelamin) yang mencoba untuk mengklaim label “feminis” dan menggunakan gerakan pembebasan perempuan sebagai wadah narsisme mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka yang mengidentifikasi sebagai “aseksual” atau “aromantis” menderita beberapa bentuk “penindasan” yang mirip dengan seksisme atau rasisme. Ini konyol dan harus diakui seperti itu.
Di balik semua kebisingan yang tidak perlu ini, perempuan dan anak perempuan masih menderita kekerasan patriarki dan laki-laki. Mari kita kembali ke makna interseksionalitas yang sebenarnya dan otentik, dan fokus pada realitas – sebagai lawan dari fantasi narsistik.
Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan posisi redaksi Al Jazeera.